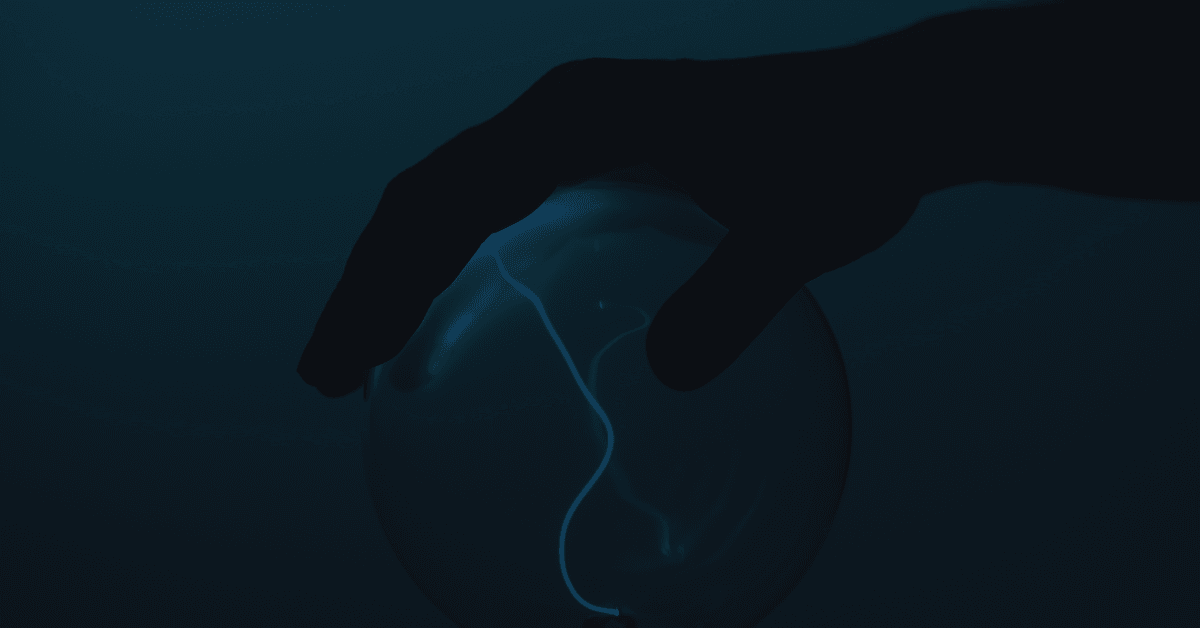Agama dan Filsafat: dua jalan hidup yang tak pernah beririsan.
Ada yang sibuk menghitung ketinggian gunung, ada yang sudah duduk menikmati pemandangannya. Begitulah perbedaan filsafat dan agama—dua cara pandang hidup yang sering saling menilai, tapi tak pernah bertemu.
Lalu, di mana kita harus berdiri?

Setiap ide besar selalu punya lawannya. Tidak ada tesa tanpa anti-tesa.
Bahkan, seringkali anti-tesa itu muncul dengan banyak sudut pandang. Seperti cermin yang memantulkan banyak bayangan, masing-masing mencoba menawarkan pandangan berbeda.
Begitu juga soal filsafat dan agama. Dua dunia yang susah sekali berjalan seiring.
Kaum filsafat melihat dunia dengan kaca mata logika. Semua harus masuk akal, semua harus dicerna oleh nalar. Sedangkan agama berdasarkan iman. Keyakinan, meski tidak terlihat, adalah landasan hidup.
Karena sudut pandang yang berseberangan, pertentangan hampir tidak pernah bisa dihindari.
Islam Liberal, Ateis, Agnostik
Pemikiran filsuf sering jadi pegangan bagi kaum Islam liberal, ateis, dan agnostik. Mereka cenderung merasionalisasi segalanya, bahkan sampai hal yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan.
Contoh paling umum: mereka bilang agama itu sumber masalah. “Lihat saja,” kata mereka, “banyak perang atas nama agama, banyak korupsi dilakukan oleh orang yang mengaku religius, banyak pemerkosaan dilakukan di pesantren.”
Benarkah?
Di sinilah letak masalah kaum liberal, ateis, dan agnostik: mereka suka menyederhanakan masalah besar untuk mendukung argumen mereka. Seolah-olah semua kejahatan adalah produk agama, padahal itu sifat dasar manusia.
Kalau dilihat lebih jernih, kasus-kasus itu bukan monopoli satu agama atau satu kelompok. Orang yang tidak beragama pun banyak melakukan kejahatan. Bahkan, jumlahnya lebih besar.
Tapi mereka sering menggunakan cara berpikir seperti itu: generalisasi.
Dari satu dua kasus, mereka membuat kesimpulan besar. Seolah semua orang beragama itu munafik.
Ada lagi yang lebih ekstrem. Mereka bilang, “Orang menginginkan apa yang ia sangkal”, dan menisbatkan ini adalah quotes dari Carl Jung. Lalu mereka berteori, orang agamis yang ingin masuk surga itu sebenarnya hanya ingin kenikmatan duniawi—yang mereka sangkal di dunia ini. (Saya akan menjelaskan ini di bawah: Catatan untuk quotes Carl Jung).
Pemikiran seperti ini seringkali membingungkan orang awam, terutama yang tidak mampu berpikir kritis, atau imannya rapuh.
Mereka punya template pemikiran yang menggiring opini. Berbahaya? Bisa jadi.
Karena logika mereka sering dipenuhi kesalahan berpikir (logical fallacy), tapi dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat benar. Argumen mereka terlihat logis di permukaan, tetapi kalau dikupas lebih dalam, sering kali hanya permainan kata.
Filsafat vs Agama Akhirnya Tak Akan Bertemu
Filsuf punya pemikiran, kaum beragama punya iman.
Dua jalur ini kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu sampai dunia ini selesai.
Bagi filsuf, kaum beragama sering dianggap “terbelenggu” oleh dogma.
Sebaliknya, bagi kaum beragama, filsuf adalah orang yang terlalu mengandalkan akal, sampai lupa ada batasnya.
Filsafat dan agama seperti dua kutub magnet yang saling menolak.
Dan bagi beberapa orang yang baru belajar, mereka akan saling memandang rendah. Menganggap bodoh pihak lain. Kenapa? Karena cara pandangnya beda. Bahkan, sering kali, bertolak belakang.
Filsuf mengandalkan logika. Semua harus masuk akal. Tidak boleh ada ruang untuk hal-hal yang tidak terjawab. Mereka terus bertanya, termasuk tentang hal-hal sakral yang dianggap dalil oleh kaum beragama.
Bagi filsuf, iman tanpa bukti logis itu absurd. Mereka melihat orang beragama terlalu mudah percaya. Terjebak dogma. Tidak kritis.
Sebaliknya, kaum beragama punya pandangan lain.
Mereka merasa filsuf itu terlalu sombong. Seolah-olah akal manusia bisa menjangkau semuanya. Padahal, ada hal yang memang di luar nalar. Yang ilahiah, misalnya. Menurut mereka, filsuf itu sering cuma muter-muter. Bicara teori. Tapi jawabannya? Nol besar.
Bagi saya, agama lebih unggul.
Saya jelaskan, dan mengajak Anda berpikir kritis, bahkan logis, seperti yang diinginkan kaum filsafat.
Kaum beragama menawarkan solusi hidup yang lebih lengkap. Agama bukan cuma bicara soal “kenapa kita ada,” tapi juga “bagaimana kita hidup.” Jelas. Praktis.
Contoh, saat hidup lagi sulit, filsuf mungkin sibuk merenung: apa arti penderitaan?
Orang beriman? Langsung jalan. Bersabar. Berdoa. Berbuat baik.
Agama memberi pegangan yang bikin tenang. Itu yang sering hilang dalam pemikiran kaum filsafat yang terlalu bergantung pada logika.
Lebih dari itu, agama mengajarkan keseimbangan.
Tidak hanya memuaskan akal, tapi juga hati dan jiwa. Orang beriman tidak terlalu lama terjebak dalam keraguan. Mereka punya kepastian: iman.
Pada akhirnya, perbedaan ini seperti dua orang yang melihat gunung dari sisi yang berbeda. Kaum filsafat sibuk mengukur tinggi gunung, menghitung lereng, dan menganalisis bebatuan. Kaum beragama, sementara itu, sudah menikmati indahnya gunung, merasakan ketenangan, dan bersyukur atas kebesaran Sang Pencipta.
Mana yang Anda Ikuti?
Filsafat dan agama tidak akan pernah bersatu. Pemikiran dan iman ibarat dua jalan paralel yang tidak akan bertemu sampai dunia berakhir.
Maka, pilihan ada di tangan Anda: mengikuti kaum liberal, ateis, atau agnostik dengan logika mereka yang begitu, atau kaum beragama yang berpegang pada keyakinan dan moral.
Clue-nya?
Lihat saja kehidupan mereka. Cara mereka bersikap, pencapaian mereka, gaya hidup, dan kondisi mental mereka. Dari sana, Anda bisa memutuskan siapa yang lebih pantas diikuti.
Ada banyak filsuf terkenal dengan pemikiran besar. Tapi, ironisnya, beberapa dari mereka justru mengakhiri hidup dengan tragis. Friedrich Nietzsche, misalnya. Pemikirannya tentang “Tuhan telah mati” begitu terkenal, tapi dia sendiri meninggal dalam kondisi gangguan jiwa.
Jean-Paul Sartre, tokoh eksistensialisme, hidup dengan pola pikir bebas, tapi akhirnya meninggal tanpa kepastian keyakinan.
Di saat sekarang, Anda bisa lihat sekeliling Anda. Bagaimana kehidupan ateis, agnostik, dan orang-orang berpaham liberal berperilaku.
Di sisi lain, lihatlah orang-orang yang benar-benar memegang nilai-nilai agama (saya ulang: orang yang benar-benar memegang nilai-nilai agama). Mereka mungkin tidak sepopuler para filsuf di dunia pemikiran, tapi hidup mereka sering lebih tenang, terarah, dan bermanfaat untuk banyak orang.
Hidup adalah Pilihan.
Memilih jalan itu soal prioritas.
Apakah Anda lebih percaya pada logika, yang sering dipenuhi keraguan?
Atau pada iman, yang memberikan ketenangan meski tidak selalu logis?
Pilihannya ada di tangan Anda.
Karena pada akhirnya, kehidupan dan akhir dari kehidupan itulah yang akan menjadi saksi dari pilihan Anda.
Terimakasih sudah membaca. Semoga bermanfaat.
Catatan untuk quotes Carl Jung:
Saya tidak menemukan bukti kutipan langsung Carl Jung yang menyatakan, “Orang menginginkan apa yang ia sangkal.” Namun, dalam teori psikologi analitisnya, Jung mengemukakan konsep “bayangan” (shadow), yang merujuk pada aspek-aspek diri yang tidak disadari atau ditolak oleh individu.
Tapi okelah, kalau mereka menisbatkan pada teori itu. Mari kita bahas.
Pernyataan kaum filsafat bahwa orang beragama, yang ingin masuk surga sebenarnya hanya ingin kenikmatan duniawi—yang mereka sangkal di dunia. Ini adalah kesalahpahaman mendasar tentang ajaran agama.
Bagi kaum beragama, surga dipahami sebagai ganjaran tertinggi bagi mereka yang menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Surga adalah tempat manusia sangat dekat dengan Sang Pencipta, bukan sekadar “tempat bersenang-senang.”
Jika seseorang meninggalkan hal-hal duniawi tertentu—seperti kesenangan yang dilarang oleh agama—itu bukan karena sangkalan, tetapi karena ketaatan. Ini adalah bentuk pengendalian diri dan kepatuhan terhadap hukum Ilahi.
Pendapat yang seolah mengutip Carl Jung tersebut juga cenderung menggunakan logical fallacy.
Ia menggeneralisasi niat orang beragama dengan pola pikir manusia secara umum, tanpa memahami nilai-nilai yang mendasari keimanan.
Dalam agama, niat seseorang diukur dari kesadaran bahwa hidup ini memiliki tujuan spiritual. Keinginan untuk masuk surga bukanlah obsesi terhadap kenikmatan, melainkan manifestasi dari harapan untuk mencapai ridha dan cinta Allah.
Sebaliknya, mereka yang memandang ini hanya sebagai upaya mendapatkan kenikmatan duniawi dengan label “surga” sebenarnya sedang memproyeksikan pola pikir materialistik mereka sendiri.
Mereka mungkin tidak memahami bahwa bagi orang beragama, kenikmatan di surga adalah konsekuensi, bukan tujuan utama.
Tujuan utama beragama dalam Islam itu simpel: ibadah kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an:
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)
Ibadah dalam Islam bukan hanya soal shalat atau puasa. Semua aspek kehidupan—akidah, akhlak, muamalah—semuanya bagian dari ibadah. Dengan beribadah, seorang Muslim berharap bisa lebih dekat dengan Allah, meraih keridhaan-Nya, dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Lalu, mengapa harus membatasi pandangan tentang surga pada kerangka berpikir duniawi? Justru ini menunjukkan bahwa pemikiran semacam itu belum keluar dari jebakan materialisme yang mereka klaim ingin hindari.